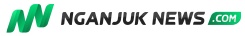Bisikan-Bisikan “Runyam” dari Tu(h)an (?)
Oleh: Yuyun Yuliana
Nganjuknews.com – Zii membenci dua orang yang duduk di
bangku dekan fakultas itu, seseorang yang selalu menekankan stereotip 'sukses'
di tiap perjalanan.
Bahkan, stigma yang dilontarkan 'mereka' untuk sebuah proses
menjadikannya hanya mampu berdiri sebagai badut - tersenyum dan berjalan tanpa
beban - meski acap kali kedua tangan menutup kuping rapat-rapat, dan menghalau
suara yang menjebol gendang telinga.
Ini semua memang di luar ekspektasi semua orang, di mana
harus ada gadis berotak cerdas yang terlahir dari dua manusia jenius.
Kendati demikian, segala yang melatarbelakangi adalah
ketidakadilan ketika Zii yang menanggung cemoohan sebagai bentuk kekecewaan.
Merupakan pandangan tabu terhadap gangguan kejiwaan dan
mental, yang menjadi salah satu masalah utama dalam pengertian masyarakat
tempat tinggal Zii, sehingga untuk tetap bisa hidup selayaknya manusia normal
merupakan keharusan yang dipaksakan kehadirannya.
Zii tahu itu. Menjadi waras adalah sesuatu hal yang
diidam-idamkan, bahkan sebelum sayatan-sayatan di pergelangan tangannya
terbentuk.
Lalu kemudian ketika malaikat maut nyaris menjemput, kata
waras malah mendadak muncul dalam dadanya. Memekakkan segala keputusasaan yang
terpendam.
Sama seperti kali ini, ketika Zii akan menemui Sang Kuasa
entah yang ke berapa kali - yang sayangnya gagal - dan malah berakhir dengan
duduk di pinggiran bangunan sekolah menengah atasnya dengan Guru Dan.
Menikmati angin malam yang serasa hambar.
“Kamu bisa bercerita dengan saya,” kalimat yang akhirnya
keluar dari bibir penuh pria berusia awal tiga puluhan itu untuk kali pertama,
tentunya setelah hening seperkian menit menemani mereka.
Zii masih enggan berucap. Ia masih mengumpulkan batas
kewarasan dalam dirinya untuk menyusun rencana-rencana kehidupan esok.
Barangkali ia bisa menjalani hidup yang normal; dan tiba-tiba berniat
menemui-Nya malamnya. Seperti saat ini.
“Ada yang mengucapkan bahwa kita harus menjadi semut baru
bisa meresapi rasa diinjak, dan harus menjadi gajah agar bisa merasa bersalah,”
tutur Guru Dan kembali.
Benar. Mungkin tak ada yang banyak bisa dilakukan pria itu
untuk menghadapi Zii - murid barunya - di sekolah yang menjadikannya pengajar
pada kurun waktu empat bulan terakhir. Zii terlalu kehilangan kewarasannya, dan
ia menyadari itu.
Perkataan dengan majas yang begitu sulit itu menarik
perhatian Zii. Ia mengembuskan napas.
“Tak perlu menjadi semut atau pun gajah untuk merasakannya,
Guru. Hanya perlu pikiran yang terbuka. Semut tak harus selalu benar hanya
karena ia kecil, dan gajah bukan berarti salah karena ia menginjak,”.
“Benar. Ada segala sudut pandang dalam melihat hal, yang
hanya dengan begitu kita tahu sedang di posisi apa,”.
Zii sontak menolehkan kepalanya, dan mengerjap ketika
disuguhi senyum lembut Guru Dan.
Ia terus-menerus memahami kalimat yang baru saja
didengarnya. Tentang menilai sesuatu dari banyak sudut pandang. Kemudian sepoi
angin membawanya pada segala hal yang seolah mendikte hidupnya.
“Kamu boleh latihan dance, tapi perbaiki dulu nilai
matematikamu,” putus pria berkacamata dengan final. Suatu hari lalu.
Zii kecil hanya melihat kepergian ayahnya - yang sayangnya
terlihat angkuh - meninggalkan ia terpuruk sekali lagi.
“Bunda selalu ngelarang Zii liburan weekend sama temen,”
marah Zii suatu sore.
Sang Bunda menatap nyalang putri semata wayangnya.
“Selesaikan tugas kamu, baru pergi."
Dan Zii kembali memeluk lututnya. Ia tersedu, merasa Ayah
dan Ibundanya hanya peduli pada nilai dan ungkapan orang.
Mungkin, kenangan itu yang terputar. Otaknya bagai kaset
rusak yang menampilkan kejadian acak dari hidup menyedihkannya.
Seolah ada banyak puzzle yang berserakan, memintanya untuk
menyusun kembali dan menemukan titik temu.
“Ceritakan apa yang kamu rasa. Saya bersedia mendengar ...
tanpa menyela,” Guru Dan kembali bersuara, menyentak lamunan gadis tujuh belas
tahun di sampingnya.
Zii termenung. Lalu bergetar lidahnya berucap, “Sa - saya
pengen sembuh, Pak,” Ia membuka kancing salah satu lengannya dan menggulung
secara perlahan hingga siku, membuat pergelangan penuh sayatan itu terpampang.
“Apakah saya bisa sembuh?” lanjutnya lirih.
Guru Dan menyimak dengan saksama. Pun sesuai janjinya,
mendengar tanpa menyela.
“Semua orang bisa menjadi berubah, terutama dalam hal yang
baik. Apa yang kamu takutkan,” tangannya meletakkan buku jurnal siswa ke
bangunan rooftop.
“Jika kamu ingin bercerita, temui saya. Setidaknya saya bisa
menjadi pendengar kamu,”
Zii menunduk. Meremas kedua telapak tangannya, lalu berganti
dengan menyentuh tiap luka goresan yang tercipta di kulit. Luka itu tampak
mencolok, kontras dengan putihnya warna permukaan kulit.
“Ayah ingin saya menjadi dosen sepertinya, sedangkan Bunda
ingin saya menjadi pengacara,” ucapnya lemah.
“Kamu ingin jadi apa?”
“Saya ingin menjadi manusia waras,”
Merasa sudah tak ada jawaban dari Guru Dan, Zii menoleh dan
mendapati gurunya itu menengadah pada langit.
“Kamu memang harus waras untuk berusaha sembuh,” jawabnya
akhirnya.
Zii membalas, “bagaimana caranya agar saya bisa waras?”
Guru Dan tersenyum. “Dengan terus bahagia,”
Sang lawan bicara bungkam.
“Hidup memang sekejam itu kah, Pak?” tanya Zii setelah
menjeda percakapan, pada akhirnya. Kemudian mengikuti gerakan Guru Dan,
menengadah pada langit. Berpikir barangkali ada ilham yang turun dari Tuhan
secara tiba-tiba.
“Hidup yang terlalu kejam atau mungkin kita yang tak
menerima. Hanya itu pilihannya,” Guru Dan kembali bersuara setelah Zii
melontarkan tanya dari tempatnya menengadah. Berkelumit dengan pikiran, mencari
sanggahan yang tepat.
Zii kemudian lagi dan lagi termenung, membiarkan ucapan Guru
Dan memenuhi otaknya bersama kewarasan yang mulai terkumpul.
Jika memaksa terus mengingat, maka memang bukan hanya
tuntutan yang dilayangkan kedua orang tuanya. Melainkan juga kasih dan seluruh
usaha memenuhi apa yang Zii inginkan.
Mungkin Guru Dan benar. Ia hanya terlalu fokus pada celah
ketidaksempurnaan tanpa memerhatikan ada banyak kubangan kebahagiaan yang
selama ini ia terima.
Zii mengutuk. Bagaimana bisa ia lupa pada siapa yang
mengajarinya naik sepeda; siapa yang menemaninya membuat kue; juga, kata
pertama yang ia ucapkan di usianya yang masih balita: Ayah, Bunda.
“Bagaimana solusi paling sederhana supaya saya bisa waras, Guru?”
Manik cokelat gadis itu berhadapan langsung dengan pekatnya
netra sang guru.
“Berdamai dengan keadaan,”
Ungkapan terakhir guru Dan, menutup fase ketidakwarasan
hidup Zii.
*****
Langit malam masih membawa hawa dingin di antara pencakar
langit ibu kota. Kesejukan yang merasuk seolah membawa jiwa-jiwa kewarasan pada
tubuh Zii.
Ia memandang langit yang menghitam dan, bintang-bintang yang
membentuk semut dan gajah. Kemudian ketika suara mobil memasuki garasi, ia
mulai menampilkan senyum semringah.
Hidup bukan akan indah pada waktunya, tetapi bagaimana kita
membuat tiap waktunya menjadi indah. Juga, tentang menerima perjalanan hidup.
Zii kemudian tahu, pada akhirnya tempat kewarasan terkumpul
adalah di keluarga. Tak peduli pada apalagi bisik-bisik komentar orang, ia
hanya akan tahu; bahwa semut tak selalu benar dan gajah tak selalu salah.
Nganjuk, 27 Desember 2022
*Penulis merupakan gadis kelahiran Juli 2003 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mulai menggeluti literasi pada akhir tahun 2019 dan beberapa karyanya telah dimuat dalam buku antologi cerpen dan puisi